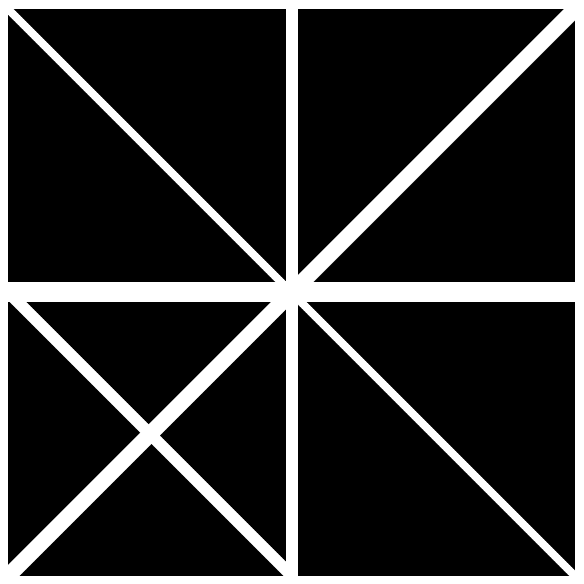Rasanya sudah lebih empat bulan sejak pertama kali saya mulai memasak sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, dan sekarang baru saya sadar kalau ternyata makan tanpa perlu memasak adalah sebuah kemewahan tersendiri –bagi orang yang tiap hari berurusan dengan pisau dan kompor.
Man, saya rasa semua orang sepakat kalau memasak itu bukan urusan yang sederhana. Tapi banyak orang yang justru menyepelekan kemewahan ini karena yang mereka lakukan hanya membayar, lalu makan. Atau bahkan makan tanpa perlu membayar (ini yang saya sebut kemewahan amat luar biasa). Kupikir manusia perlu untuk ditelantarkan sendiri di tengah lautan, tanpa kawan, hanya perahu, kail pancing, korek, dan kayu bakar. Supaya ia alami sendiri betapa tidak enaknya lauk yang ia makan, tapi ia tidak punya pilihan lagi.
Empat bulan yang lalu saya memang tidak punya pilihan selain memasak. Hampir semua warung makan tutup karena pandemi, sementara mulut kelaparan tidak berhenti mengaum di sekitar saya. Sekarang saya punya pilihan, dan saya memilih untuk tetap memasak. Mulai timbul kesadaran pada diri saya bahwa meramu makanan sendiri adalah jalan yang benar untuk saya, dan alam semesta.
Dengan memasak sendiri saya jadi lebih peduli terhadap tiap senyawa yang masuk ke dalam tubuh saya. Sejak kecil saya dibiasakan untuk mengonsumsi makanan tanpa penguat rasa artifisial. Mulai sekarang saya juga mengurangi konsumsi daging unggas dan pemamah biak. Saya bisa menghabiskan 40-60 menit di pasar swalayan demi mempelajari setiap informasi yang tertera di bungkus makanan (selalu iseng dan kompulsif baca ingredients, produsen, asal negara, sama ngitung harga per gramnya). Saya juga harus paham betul perilaku tiap bahan makanan, selisih satu langkah aja udah pasti beda rasanya.
Satu hal paling penting yang meyakinkan saya untuk masak sendiri adalah saya bisa menentukan sendiri apa yang enak dan tidak enak menurut lidah saya, bukan lidah orang banyak. Secara tidak sadar makanan yang disajikan di warung-warung sekitar kita adalah makanan yang monoton, mi instan misalnya. Menu ini hampir selalu ada di tempat nongkrong kekinian, yang malas untuk menggali orisinalitas, dan menyerah pada selera pasar. Mulai jenuh saya dengan kehadiran warung kopi baru setiap bulannya, tapi giliran buka lamaran semua minta pengalaman kerja minimal setahun. Babik.
Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan.