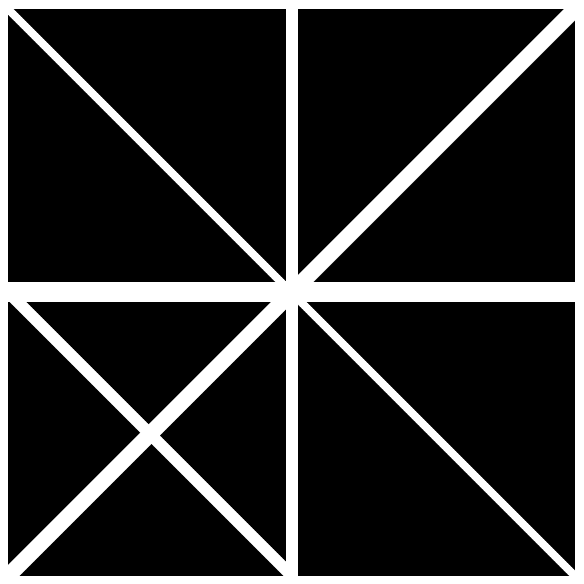Sudah tiga hari ini aku kecanduan mendengarkan FSTVLST dan rasanya amburadul ―hancur lega riang sendu prihatin menjadi satu. Kemagisan ratusan malam yang pernah kuhabiskan di Jogja tiba-tiba menyeruak masuk di antara sunyi senyap langit lintang selatan.
Ingatanku tentang jogja belum begitu usang, sebagian besar terisi oleh semrawut perbincangan di bawah temaram lampu angkringan, atau sepintas percakapan para manusia berpelindung kepala di atas roda dua yang samar terdengar di antara deru mesin, atau sesekali juga sayup alunan pesindhen menembang macapat dalam iringan bonang dan kendang.
Seandainya dulu aku melanjutkan kuliah seni bangunan di Bandung, mungkin aku tidak akan pernah menyaksikan bagaimana ikatan kebatinan antarproletar di bumi Mataram bisa terbentuk sedemikian solid tanpa perlu didefinisikan. Aku memang bukan terlahir sebagai kaum marginal, namun separuh nyawaku barangkali berasal dari sana ―bongkahan lemah yang tak akan pernah diperhitungkan sejauh apapun mata memandang. Ia menyeretku kemari, menyalakan sinyal agar dapat bersilangan tapak dengan mereka yang terus hidup dan menghidupi, walau tak bernaung tak berarah.
Kumpulan syair Farid Stevy di album Hits Kitsch menjadi pengingat buatku untuk tidak meromantisasi si kota gudeg ini dengan narasi berhati nyaman, yang kerap menjelma jadi jargon mereka yang hendak mengakumulasi kapital garis miring kuasa. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan ungkapan nostalgia yang diasosiasikan kepada Jogjakarta, hanya saja ia seringkali menyesatkan batin dan pikiran.
Orang-orang yang pernah tinggal atau sekedar berkunjung ke kota ini selalu berharap bahwa segala yang indah tidak berubah, tetap seperti yang telah tersimpan rapih dalam arsip kenangannya masing-masing. Mereka kerap dibikin tersesat dalam ingatannya sendiri sehingga sulit memilah antara yang fana dan yang nyata. Apakah memang sesuatu di Jogja yang menjadikannya istimewa ataukah kita yang mengistimewakan Jogja karena sesuatu? Sampai sekarang pun aku masih belum bisa berdamai dengan satu fakta yaitu: ketika suatu hari aku berkunjung ke kedai bakmi jawa langgananku, aku tidak akan lagi bisa bertukar cerita dengan tukang masaknya.
Disinilah aku mulai mengutuk golongan yang suka mengeksploitasi perasaan manusia demi keuntungan semata. Mereka tahu bahwa orang luar yang ‘pulang’ ke Jogja tidak akan menemukan sesuatu yang dicarinya, sehingga mereka bangun objek wisata, warung kopi, atau rumah makan baru untuk sekedar mengobati para insan yang hampir sekarat karena hampa. Sebagian dari mereka juga yang gemar menciptakan fragmentasi lahan pertanian untuk pengembangan hunian demi mengakomodasi orang-orang yang bermimpi hidup ala wong yogjo. Padahal kerinduan tidak selamanya harus dikomodifikasi seperti itu, biarlah sawah menjadi sawah dan kebun menjadi kebun, begitu pun semak-semak rimbun di tepian sungai. Kalau memang transformasi adalah sebuah keniscayaan, mengapa sulit sekali melihat ada yang berubah untuk urusan transportasi umum dan upah minimum?
Agaknya kita perlu ingat bahwa Jogja terbentuk dari belas kasih penghuninya yang selalu ringan memberi teduh untuk mereka yang datang dan pergi. Namun, akankah kita mencapai sadar bahwa kebaikan yang tumbuh dari ketidakseimbangan tentu akan mencapai nadirnya pada suatu titik di garis waktu. Reproduksi pengetahuan pun suatu saat dapat menggeser nilai-nilai kearifan, bahkan meruntuhkan struktur sosial yang telah terpancang kuat. Dan ketika semua itu terjadi, aku berdoa agar Jogja tetap diberkati menjadi Tanah yang indah untuk para terabaikan rusak dan ditinggalkan.