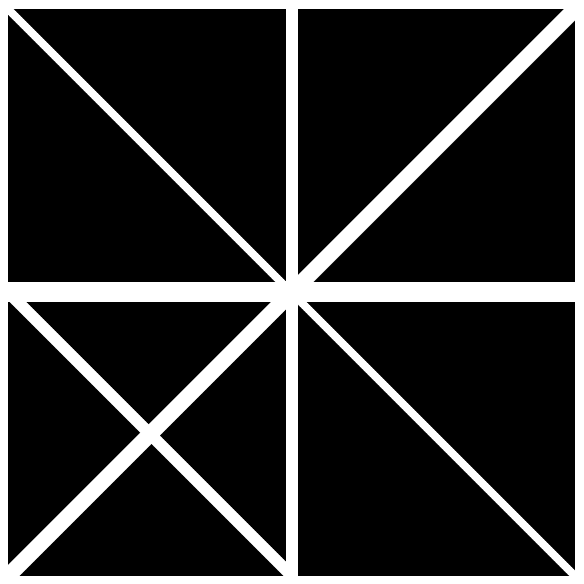Sejak semalam beranda media sosial orang Indonesia digemparkan oleh satu poster peringatan darurat berlambang garuda pancasila dengan latar biru. Konteksnya adalah, Badan Legislatif DPR RI baru saja melakukan manuver untuk merevisi UU Pilkada dalam beberapa jam setelah putusan MK tentang ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Aku yang sedang terduduk syahdu di toilet pun langsung memuntahkan sumpah-serapah ketika membaca berita ini, mengutuk seisi istana dengan umpatan berbagai jenis penghuni kebun binatang, lalu tertawa, gila, dan akhirnya kembali menatap layar untuk merampungkan esai. Aku tahu kalau keesokan harinya pasti akan ada demo besar-besaran karena luapan emosi masyarakat yang tak terbendung menyikapi ketidakpastian hukum beberapa waktu belakangan. Publik mulai terbuka akan sikap politiknya dengan me-repost peringatan darurat ini tanpa memerdulikan personanya di media sosial ―kecuali aparatur sipil negara yang barangkali mulutnya masih terbungkam oleh kaki tangan culas pemerintah. Aku senang karena orang-orang mulai menyerukan untuk lantang berbicara, namun aku punya alasan pribadi untuk tidak me-repost gambar garuda berlatar biru atau ujaran kedaruratan lainnya.
Pertama karena aku melihat kebanyakan orang sepertinya latah dalam merespons emosinya di media sosial. Beberapa bulan yang lalu ketika Rafah dibombardir oleh serangan udara Israel, netizen pun ramai mengunggah gambar bertuliskan “All Eyes on Rafah“, yang konon jumlah postingannya mencapai puluhan ribu. Satu tindakan kecil memang akan menghasilkan dampak yang signifikan bila dilakukan bersama, tapi bukan berarti kita dapat terlepas dari urusan moral selepas menunaikan tindakan kecil tersebut. Kemana kah mata kita tertuju saat tragedi kemanusiaan masih berlangsung di Gaza hingga hari ini? Satu hal yang barangkali luput dari kesadaran kolektif manusia digital adalah tentang bagaimana memaknai rentetan peristiwa duka lebih dari sekadar reaksi momentual belaka. Tentu saja tidak ada manusia yang sanggup untuk terus menerus larut dalam suasana berkabung, atau terus menerus dilanda kekecewaan atas kondisi struktural yang berada di luar jangkauannya, namun penting bagi kita untuk menolak lupa atas segala kejadian yang berkecamuk di luar ambang batas kewajaran. Sekarang coba tengok lagi empat tahun ke belakang, masihkah kita sudi mengingat berapa ribu nyawa manusia yang seharusnya dapat terselamatkan jika negara bertindak sedikit lebih serius dalam menangani pagebluk?
Kedua, meskipun sejak awal Najwa sudah berpesan bahwa ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaesang ataupun PDI Perjuangan, aku tetap tidak terima jika Mak Banteng kemudian menunggangi kemarahan rakyat ini sebagai kendaraan politiknya. Seakan posisinya sebagai oposisi tunggal dalam parlemen ekuivalen dengan keberpihakannya terhadap kepentingan ‘rakyat kecil’. Dia anggap masyarakat sudah lupa bahwa fraksi merah lah yang dulu pernah mendorong revisi UU MD3 dan meloloskan RUU Cipta Kerja secepat kilat. Padahal kami semua pun telah mafhum bahwa partai-partai saling berkoalisi untuk mengamankan cengkeraman kuasa di tingkat provinsi atau kabupaten di luar Jakarta. Tidak ada elit yang dapat benar-benar dipercaya, sehingga tidak ada boleh mencuri panggung perjuangan demokrasi atas nama rakyat! Tai kucing jika aku dapati ada anggota DPR yang memasang poster garuda berlatar biru di akun media sosialnya.
Ketiga, aku mengamati kesenyapan perlawanan dari kawan-kawanku yang bertempat tinggal jauh dari kota-kota besar. Kesenyapan ini tidak serta-merta menunjukkan kepuasan mereka terhadap hasil kerja pemerintah, melainkan adalah sebuah gambaran bahwa selama ini aglomerasi gagasan tentang bangsa dan negara adalah milik orang-orang kota saja. Bukan sekali dua kali aku mendengar kawanku di desa berpendapat bahwa mereka acapkali hanya bisa menjadi penonton ketika ribuan orang tumpah ruah di jalanan, karena memang hanya di kota orang-orang bisa memiliki ruang untuk melawan. Sementara di desa, semua ruang telah terokupasi untuk akumulasi kapital, dan perlawanan tidak pernah mendapat sorotan yang berimbang. Siapapun yang berada di puncak kekuasaan dan bagaimanapun bentuk pemerintahan diperdebatkan, tidak akan mengubah fakta bahwa masyarakat desa hanya akan dikunjungi sesuai kepentingan. Peduli setan dengan penghidupan para petani dan nelayan yang mulai terancam krisis lingkungan, aku yakin demonstran pun enggan datang. Bagiku, menolak memasang garuda berlatar biru adalah bentuk solidaritas kepada mereka yang terabaikan dan ditinggalkan.
“Biar lah kamu orang di ibukota sana saling ribut, baku hantam, pun setelah semuanya usai hidup kami akan tetap seperti ini saja”.
Keempat, aku merasa ada hal lain yang dapat aku lakukan agar tidak dicap fomo oleh orang-orang kerumunan. Sama halnya dengan seniman yang mengambil jalan perlawanan melalui karya, atau wartawan yang berjuang melalui liputan, aku pun seutuhnya yakin bahwa mahasiswa dangkal sepertiku juga bisa memaknai rentetan peristiwa ini walau hanya melalui catatan. Selain itu, aku juga percaya bahwa orang-orang di sekelilingku pasti sudah tahu kalau aku tidak akan tinggal diam atas semua yang sedang terjadi, sehingga tidak perlu lagi untuk menguraikan panjang lebar tentang keberpihakanku di sosial media. Seandainya demonstrasi di depan kedutaan besar adalah tindakan yang relevan, pasti sudah aku lakukan, sayangnya ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan kedutaan. Banyak kawanku juga merasa asing karena tidak memiliki kanal untuk berteriak “ANJING!” di hadapan anggota dewan, seandainya bisa, mungkin kami sudah terbang ke Jakarta dan saling berpegangan erat dalam barisan. Tapi tentu saja kami mahasiswa selalu menemukan bentuk perlawanan yang sepadan, panjang umur perjuangan.

Woden, 22-VIII-24