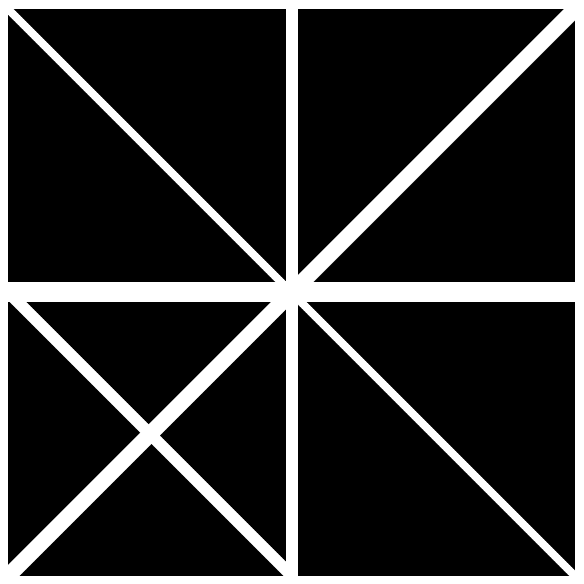Di penghujung semester dua, aku sedikit banyak mulai memaknai pengalaman berkuliah di sekolah kebijakan publik, yang intinya adalah tentang belajar caranya masuk ke dalam pembicaraan para pembuat kebijakan. Seperti memasang antena di kepala, telingaku menjadi bising oleh sinyal-sinyal dari frekuensi yang terdengar janggal. Butuh energi lebih rasanya untuk sekadar menjaga kewarasan jiwa, yang ternyata rekan sejawatku juga mengamini hal yang sama. Bukannya apa, tapi seseorang bisa jadi sangat emosional saat menyelami diskursus studi lingkungan karena apa yang dibahas di dalamnya menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak, atau, mungkin dalam lingkup terkecil ia menentukan strategi bertahan hidup sekelumit orang yang kita cintai. Kadang aku menduga apa yang dibicarakan di kelas itu hanyalah kumpulan muatan abstrak yang bergumul dalam kepala mereka yang terlampau cerdas, jauh dari keseharianku yang agaknya terasa biasa-biasa saja. Dari dasar lubuk hati aku berharap bahwa semua ramalan tentang bencana iklim dan hancurnya kemanusiaan adalah dongeng belaka, namun semuanya terlalu nyata untuk disangkal. Ujung-ujungnya aku akan terjebak dalam pertanyaan mengenai eksistensi umat manusia yang seakan sedang berjejalan menuju jurang kematian. Tapi mengapa juga aku perlu terjebak disana, sementara jawaban dari apa yang bijak dalam kebijakan pun aku tidak paham.
Seringkali aku dibuat kagum dengan bagaimana para akademisi mampu menggambarkan suatu fenomena dengan konsep-konsep alien seolah mereka adalah makhluk asing yang tengah membicarakan bagaimana dunia manusia bekerja; sebenarnya engkau ini setan atau malaikat? Segala hal tentang komodifikasi, dekolonisasi, pascapolitik, neoliberalisme, serta sederet konsep asing lainnya secara implisit mencoba mengatakan bahwa cita-cita menjadi juru penyelamat bumi adalah naif, mengharapkan kemanusiaan dan keadilan adalah utopis. Tidak ada permasalahan lingkungan yang berdiri tunggal, mereka semua saling terikat oleh rasa serakah, lalu kusut akibat kejemawaan manusia yang merasa mampu mengatur segalanya. Tidak bisa kah kita berdiam sebentar lalu berserah; sadar bahwa tidak semua yang ada perlu dimiliki dan tidak semua yang rusak perlu diperbaiki. Apakah aku sedang menjelma jadi alien ketika membicarakan tentang manusia? Kadang aku khawatir demikian.
Woden Valley, 02-XII-24