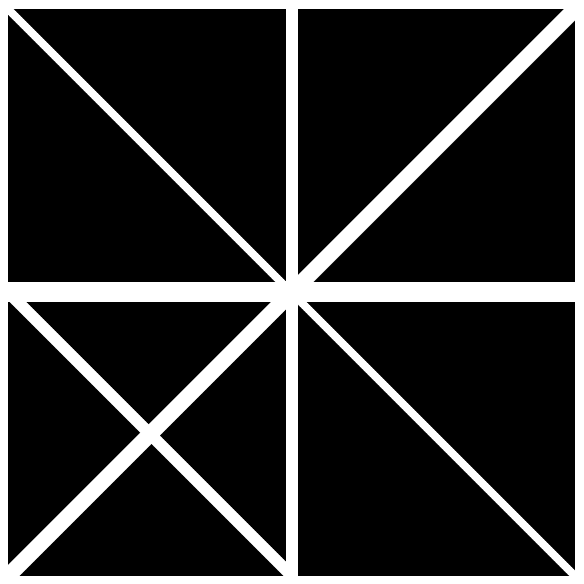Di tengah kesibukan dunia merampungkan tesis, aku pilih menonton. Judulnya “Like father, like son” karya Hirokazu Kore-eda. Tanpa pikir panjang langsung kuberikan bintang lima. Ceritanya sangat personal, tentang dua keluarga yang tiba-tiba mendapat kabar dari rumah sakit bahwa anaknya tertukar pada saat proses persalinan. Fenomena seperti ini rupanya cukup jamak terjadi di era pascaperang Jepang tahun 1960-an. Sehingga menarik bagaimana sang penulis menarik premis dari hal yang mulanya sempat dimaklumi masyarakat, namun hari ini dianggap sebagai kejanggalan luar biasa.
Kejadian ini digambarkan saat Keita berumur 6 tahun. Ayahnya, Ryota, adalah tipikal arsitek pekerja keras yang mengedepankan nilai kedisiplinan dan independensi dalam mendidik anak. Nilai ini ditanamkan kepada anaknya secara tidak langsung melalui rutinitas les piano, etika menggunakan sumpit, pembatasan jam bermain, serta kode etik untuk tidak berada dalam satu bak mandi bersama anaknya. Namun karena kesibukannya sebagai arsitek, peran mengasuh anak ia limpahkan kepada istrinya. Sampai tamat taman kanak-kanak, Keita lebih banyak meghabiskan waktu dan tumbuh bersama ibunya di apartemen. Struktur patriarkal masyarakat Jepang juga tercermin dalam berbagai dialog antara Ryota dengan istrinya, Midori. “Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? padahal aku sendiri adalah ibunya.”
Sementara Ryusei, anak Ryota yang tertukar, dibesarkan dalam lingkungan yang jauh berbeda. Ia tinggal di kota kecil bersama dua orang adik. Ayahnya, Yudai, mengelola toko perlengkapan listrik secara mandiri di rumah, dan ibunya, Yukari, bekerja di sebuah kedai ramen. Kepribadian Yudai sangat bertolak belakang dengan Ryota, tipikal ayah yang penuh energi meladeni anak kecil namun kurang cakap dalam urusan formal, apalagi menghasikan uang. Kritik tentang etos ‘kerja keras’ Jepang juga beberapa kali diselipkan oleh Kore-eda dengan cara menyandingkan Ryota dan Yudai dalam mengelola waktu sehari-hari. Yukari juga sangat berbeda, sebagai ibu anak tiga ia menerapkan gaya asuh yang lebih koboi dibandingkan Midori yang cenderung protektif.
Seusai berurusan dengan pihak pengadilan, kedua keluarga pun sepakat untuk menempuh langkah tukar anak. Disini kita dapat menyaksikan bagaimana dinamika antarkelas sosial turut memengaruhi cara masing-masing keluarga berdialektika menavigasi keinginan dan perasaan. Pertanyaan seputar pewarisan sifat dan makna kemiripan fisik dalam relasi antara orangtua dengan anak menjadi perenungan sentral dalam film ini. Kore-eda memang paling handal menyajikan paradoks melalui keluguan anak kecil.
Satu diantaranya adalah ketika Ryusei menyoal tentang panggilan ‘ayah-ibu’ ke Ryota dan Midori. Seandainya pun Ryota bisa menjelaskan duduk perkara saat persalinan di rumah sakit, belum tentu hal tersebut dapat membuat Ryusei percaya tentang siapa orang tua yang sebenarnya. Di sisi lain, Keita yang nampaknya cukup menikmati waktunya bersama Yudai dan Yukari, tetap saja diliputi perasaan yang janggal. Entah kecewa atau trauma, ia selalu berusaha menghindar ketika mengetahui Ryota datang berkunjung. Mungkin dalam hati Keita juga diselimuti pertanyaan “Kenapa aku harus melakukan ‘misi’ ini? Kenapa hubungan darah menjadi lebih penting ketimbang rasa sayang yang tumbuh secara alami?“
Pada suatu adegan ketika keluarga Keita dan Ryusei pergi berkemah bersama di pinggir sungai. Ada satu percakapan antara Ryota dan Yudai yang sangat berharga tentang berdamai dengan masa lalu. Yudai membuka percakapan dengan ajakan bermain layangan. Ia mengeluhkan permainan layangan zaman sekarang yang terlalu mudah, padahal merakit layang-layang yang bisa terbang sempurna adalah tantangan tersendiri. Saat Yudai bercerita tentang kenangan bermain layangan bersama ayahnya, Ryota menjawab secara singkat “Ayahku bukan tipe yang mengajak anaknya bermain layang-layang.” Ekspresinya mengisyaratkan dua hal, antara ungkapan kekecewaan atau menekankan perbedaan.
“Tapi kan kamu tidak harus menjadi seperti ayahmu.” – Yūdai Saiki
Setelah dewasa aku senang bisa merefleksikan pengalaman ini. Aku sendiri merasa amat dekat dengan pengalaman Keita sebagai anak yang sama-sama tinggal bersama orangtua non-biologis dan mendapatkan dukungan fasilitas belajar yang lengkap. Tentang identitas yang disembunyikan bertahun-tahun, tentang konstruksi sosial mengenai relasi anak dengan orang tua, dan tentang ekspektasi mengenai keluarga yang sempurna.