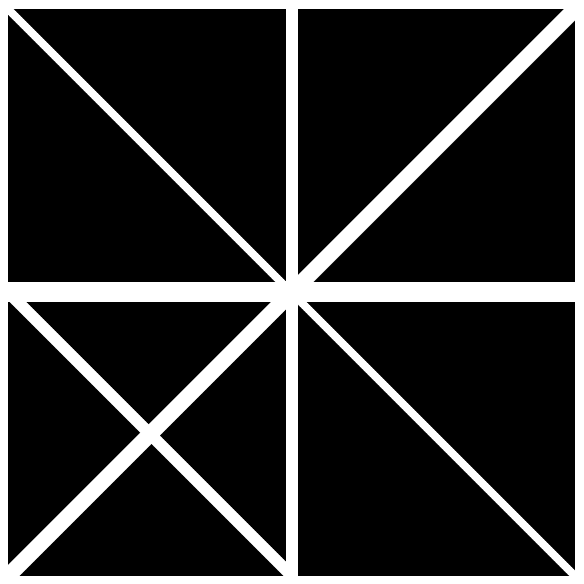Harus aku akui bahwa belakangan ini aku sedang amat membenci semerbak hembusan gas yang keluar dari belakang tubuhku sendiri, sampai pada taraf dimana aku sudah benar-benar muak hingga ingin unsubscribe. Awalnya sih tidak masalah, karena kupikir gas itu hanya akan beraroma busuk dalam beberapa jam atau hari saja. Biasanya ini adalah mekanisme alami yang mengingatkanku untuk segera pergi ke jamban dan menguras habis semuanya. Namun ini sudah lebih tiga minggu dan kentutku masih saja selalu bau! Sial, seandainya saja ada teknologi celana dalam yang dapat menetralisasi amonia dari gas buangan manusia, mungkin saat ini aku bisa menjalani hari dengan lebih tenang. Aku mendapati diriku sendiri terjebak dirundung oleh aib aroma busuk yang aku sendiri tidak tahu bagaimana cara lari darinya. Bangkai!
Kalian harus tau kawan kalau baunya itu bukan seperti bangkai yang tajam menusuk dari radius tujuh meter; ia lebih sopan karena hanya dapat dihirup jika hidungmu berjarak setidaknya satu meter dari sumber aroma. Jadi untuk bisa ikut merasakannya, kamu harus cukup dekat denganku; bisa dengan duduk bersebelahan atau berdiri dengan saling memandang. Tapi tenang, ia selalu keluar bersamaan dengan suara ‘duut‘ untuk menarik perhatian, meskipun kadang ia juga menyelinap tanpa permisi. Aku juga sudah menghitung dan mengamati kecenderungan gas ini bergerak dengan kecepatan normal 0.3 m/s, cepat atau lambatnya tergantung dari dorongan yang diberikan. Artinya, seseorang memiliki waktu 2 detik untuk menentukan apakah hendak pergi menjauh atau menikmati gas ini bersama-sama.
Bukannya bermaksud menyombongkan diri, tapi gas yang aku keluarkan ini sudah tersertifikasi organik, sangat natural dan sangat membumi seperti berasal dari bahan-bahan alami yang biasa tersaji di meja makan. Kadang aku juga suka terheran-heran sendiri saat menebak catatan aroma yang dihasilkan dari gas buangku. Pada sentuhan saraf olfaktori yang pertama aku sering mendapati bau busuk yang mengingatkanku pada comberan tersumbat yang di permukaan airnya terdapat lapisan buih berwarna hijau, lalu pada sentuhan berikutnya aku menemukan aroma pisang keju. Di lain hari, aku mendapatkan top note aroma Indomie goreng rendang dengan base note kaus kaki berkeringat yang baru saja dilepas setelah seharian bekerja. Namun yang paling aku benci adalah ketika ia menjelma anyir keramaian di pasar ikan yang tidak jelas muasalnya apakah dari cumi kering, teri asin, atau ketiak orang yang mondar-mandir bawa buku kwarto dan pulpen. Satu hal yang pasti dari ragam aroma gas buangku adalah ia menyiratkan jejak sisa makanan semalam, atau kemarin lusa, atau seminggu yang lalu; selalu menjadi sebuah teka-teki.
Bagaimanapun itu, aku meyakini bahwa gas buang yang diproduksi oleh setiap insan memiliki karakteristik tersendiri. Aku pernah membuktikan hal ini ketika tujuh tahun yang lalu aku bersama lima orang kawanku pergi ke dataran antah berantah yang mengharuskan kami untuk berkemah selama empat belas hari bersama. Selama kurun waktu tersebut, kami memang jarang buang air besar karena sulit menemukan semak-semak untuk bersembunyi. Jika pun ada lokasinya nun jauh ujung horizon padang rumput, ditambah lagi masing-masing harus bergantian membawa perkakas gali dan kubur. Sehari-hari kami hanya mengonsumsi buah, coklat-prem, susu dan roti yang berpadu dengan selai, atau daging olahan, atau telur. Kami pun selalu menyantap makanan pada jam yang sama, sehingga akan ada saatnya dimana perut kami semua bergejolak bersama-sama. Bila mungkin kami akan saling menghindar, selebihnya ya terpaksa ditelan saja toh gas buang yang kami hasilkan punya aroma yang hampir identik. Tapi anehnya, saat semerbak gas itu mengudara tanpa suara, kami bisa yakin mengenai siapa produsennya. Mulanya memang melalui tebakan secara acak yang sering salah, tapi setelah lama bersama, kami mulai mengasosiasikan aroma dengan ingatan tentang muka. Mungkin suatu saat jika aku berjumpa dengan kawananku ini, yang kurindukan tidak lain adalah bau kentutnya.
Woden Valley, 16-I-25